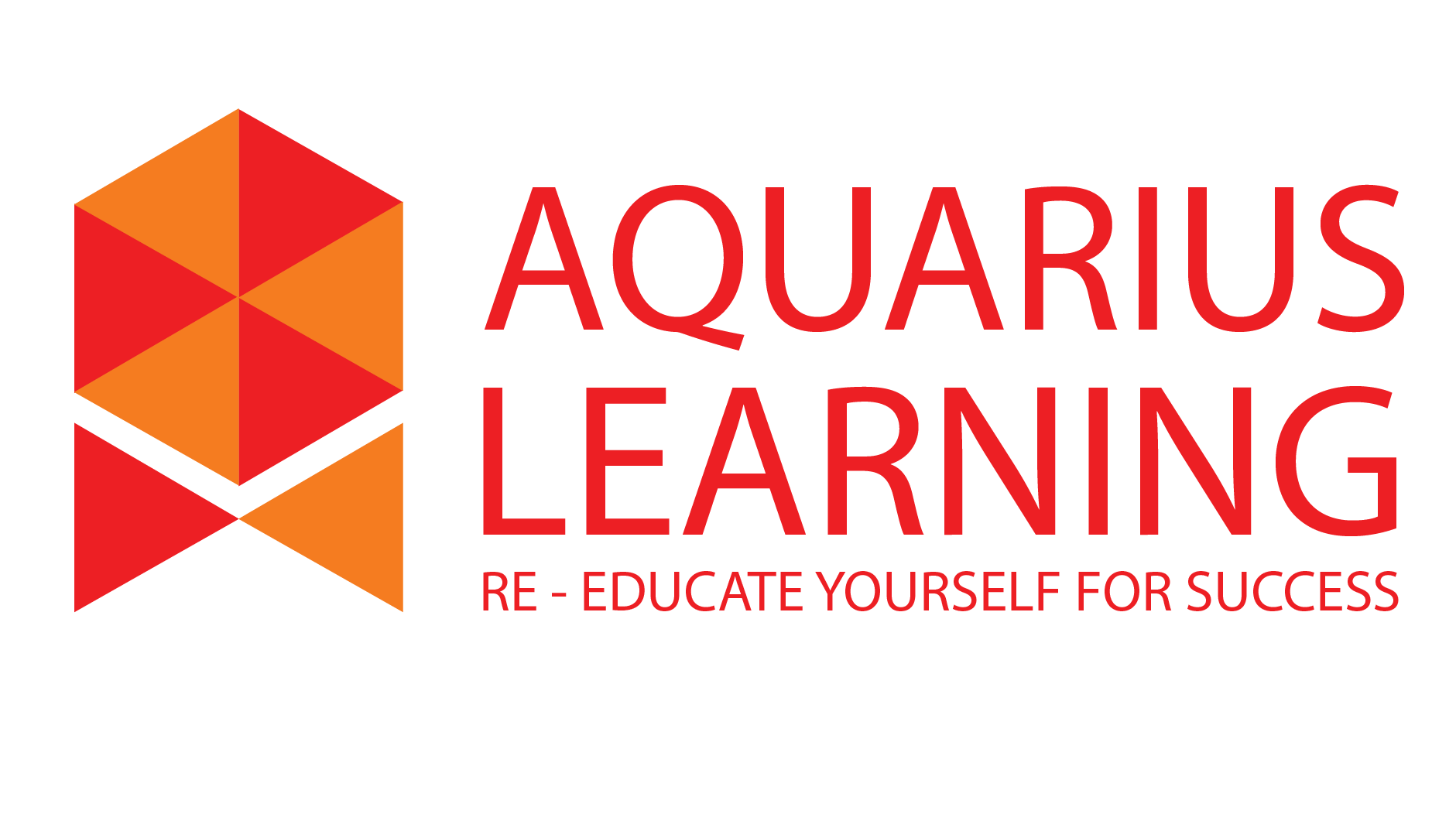Andai aaaaaku jadi orang kaya
Andai aaaaangga usah pake kerja
Pengen punya mobil, mewah
Lengkap dengan AC, tape, dan sopir pribadi
Hehehe, begitulah impian kita. Kita semua ingin menjadi orang yang sukses, kaya, dan terpandang. Memiliki hidup yang kaya dan sukses merupakan sebuah pencapaian. Dan, ini bukan sesuatu yang salah.
Akan tetapi, ironisnya, setelah mencapai semua itu, ternyata hidup kita tidak kunjung bahagia. Kita, yang tadinya meyakini bahwa semua masalah akan selesai ketika kita kaya raya, ternyata mendapati diri kita masih berkubang kesengsaraan setelah memiliki semua yang kita impikan.
Melihat kenyataan ini, kita pun lantas berkesimpulan bahwa harta bukanlah segalanya. Harta tidak membuat kita bahagia. Lebih jauh, kita berkesimpulan bahwa kebahagiaan tidak ada kaitannya dengan harta.
Kesimpulan ini memang benar. Yup! Kita semua sepakat bahwa harta bukanlah segalanya. Ia bukanlah penentu kebahagiaan. Semakin banyak harta tidak berarti kita semakin bahagia.
Akan tetapi, yang perlu dicatat, kesimpulan ini terkadang disalahtafsirkan oleh sebagian orang. Banyak dari kita yang lantas antipati terhadap harta, dan memilih untuk hidup sederhana dan menjauh dari kehidupan sosial. Mereka mengisolasi diri dan menolak modernitas dan segala hiruk-pikuknya. Ada juga yang lantas menghakimi orang yang berusaha untuk meraih kesuksesan finansial sebagai orang yang terlalu mengejar dunia dan tidak pernah bersyukur dengan yang ia punya.
Dalam hal ini, bukan fokus penulis untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Dalam tulisan ini, penulis ingin berbagi pandangan bahwa semakin banyak harta bukan berarti kita semakin bahagia. Lebih jauh, dalam tulisan ini, penulis ingin berbagi pandangan mengenai ada tidaknya hubungan antara materi dan kebahagiaan, juga apakah kebahagiaan berhubungan dengan pikiran kita dan bagaimana meraih kebahagiaan yang sesungguhnya.
Well, sekarang langsung saja kita simak penjelasan berikut.
Syarat Pertama Kebahagiaan
Di atas tadi penulis katakan, banyak orang yang salah menafsiri kesimpulan bahwa semakin banyak harta tidak lantas membuat kita semakin bahagia.
Lalu, di mana letak salah tafsirnya? Kita harus mengakui kenyataan bahwa hidup kita dibatasi oleh fisik dan lingkungan. Untuk bertahan hidup kita butuh pangan, papan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, kita butuh sandang dan pendidikan. Jika kita antipati terhadap harta dan memilih untuk mengisolasi diri dari lingkungan, bisa dipastikan kita tidak akan bisa bertahan hidup.
Supaya lebih jelas, mari simak ilustrasi berikut. Andaikan kita menolak harta dengan kerja seadanya. Celakanya, kita merupakan bagian integral dari masyarakat. Kita harus mengikuti aturan masyarakat jika masih ingin bertahan hidup. Kita memiliki rumah, bukan berarti kita gratis hidup di rumah tersebut. Kita wajib membayar pajak untuk rumah kita. Jika kita hendak bepergian, kita butuh alat transportasi. Kita harus membayar untuk dapat menaiki alat transportasi tersebut. Atau, jika kita memiliki alat transportasi, kita perlu membeli bahan bakar untuk meghidupkan mesinnya.
Saat istri kita sakit, kita perlu membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Dan, kita pun membutuhkan biaya untuk menyembuhkannya. Demikian juga untuk keamanan dan pendidikan anak-anak kita. Tidak mungkin kita mendapatkan semuanya tanpa harta.
Bagaimana jika kita meninggalkan semua kebutuhan itu? Kita tidak mungkin tidak memiliki kebutuhan itu karena semua itu merupakan syarat hidup. Kita butuh makan, kita butuh sandang untuk melindungi tubuh kita dari panas dan dingin. Kita juga butuh papan alias rumah untuk melindungi diri kita dari hujan, panas, dan privasi kita. Kita juga butuh jaminan kesehatan. Untuk mendapatkan semua itu, kita butuh harta alias uang.
Lebih jauh, saat kebutuhan pokok kita tidak terpenuhi, mustahil kita akan bahagia. Bagaimana kita akan bahagia jika perut kita kosong? Bagaimana kita akan bahagia jika istri kita sakit sementara kita tidak memiliki uang untuk membawanya berobat? Bagaimana kita akan bahagia jika anak-anak kita menggigil kedinginan di tengah hujan? Dalam hal ini, kita dapat menyimpulkan hubungan antara harta dan kebahagiaan, yaitu bahwa kita akan bahagia manakala kebutuhan pokok hidup kita tercukupi. Dan, karena di jaman sekarang, untuk memenuhi kebutuhan pokok kita perlu harta alias uang, maka dapat disimpulkan bahwa untuk bahagia kita perlu harta!
Ini bukan berarti penulis menghakimi bahwa saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki kebahagiaan. Penulis yakin, mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan memiliki cara mereka sendiri untuk membahagiakan diri sendiri dan keluarganya. Dengan terus bersyukur, berpikir positif, dan menerima pemberian Tuhan, tanpa terus mengeluh, paling tidak penderitaan mereka berkurang.
Tetapi, perjuangan untuk hidup tidak lantas berhenti hanya dengan bersyukur, berpikir positif, dan tidak mengeluh. Lebih jauh, kita harus terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena, jika tidak, kita tidak akan bertahan hidup. Bagaimana pun kita pandai bersyukur dan tak pernah mengeluh, jika kita tidak mengimbanginya dengan berjuang memenuhi kebutuhan hidup, kita tidak dapat bertahan hidup. Perut yang kosong butuh untuk dikeyangkan. Sakit yang menyerang butuh untuk disembuhkan. Gigil di malam hari butuh dihangatkan dengan rumah, kamar, dan selimut.
Untuk itulah, selain bersyukur, kita wajib bekerja! Kebutuhan pokok kita merupakan motivasi yang mendorong kita untuk terus bermimpi dan berkarya. Bahkan, dengan dorongan pemenuhan hidup inilah, dari yang awalnya kehidupan kita primitif, pada akhirnya kita menjadi masyarakat yang maju dan berbudaya.
Nah, lantas mengapa saat kebutuhan kita tercukupi dan bahkan saat memiliki harta yang melimpah kita masih sengsara? Untuk menjawab itu, mari kita simak penjelasan berikut.
Syarat Kedua Kebahagiaan
Thomas Sterner, penulis buku The Practicing Mind yang termasyhur itu, dalam bukunya menulis:
“All cultures begin by expanding their energy and resources on survival. If a culture survives its fancy, its people eventually pass the point of having to spend all their time focusing on staying alive. They get to a point where they can ask what’s for dinner, instead of asking whether there’s dinner. Their days have more free time. It is at this point that the society faces a fork in its road. We have been standing at this fork for quite some time. On one path, you can spend at least a portion of this free time on expanding your spiritual awarness, your knowledge of your true self. The other path leads away from this truth into an endless cycle of meaningless self-indulgence that, at its core, is an attempt to fill the spiritual void that many of us experience in our lives.”
Inti dari apa yang ditulisnya di atas yaitu bahwa kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan pokok yang bersifat fisik. Kebahagiaan juga ditentukan oleh kebutuhan spiritual. Yang perlu kita perhatikan, kebutuhan spiritual erat kaitannya dengan pikiran kita. Terpenuhinya kebutuhan spiritual tergantung pada bagaimana kita mengolah pikiran kita.
Kembali pada kebutuhan pokok fisik dan kebutuhan spiritual, hubungan antara kebutuhan pokok fisik dan kebutuhan spiritual yaitu bahwa kita tidak akan bahagia hanya dengan memenuhi kebutuhan pokok fisik. Demikian juga, kita tidak akan bahagia hanya dengan memenuhi kebutuhan spiritual kita. Syarat kebahagiaan adalah terpenuhinya dua kebutuhan tersebut. Yang wajib dipenuhi pertama adalah kebutuhan pokok yang bersifat fisik. Setelah kebutuhan pokok fisik terpenuhi, kita masih perlu memenuhi kebutuhan spiritual.
Hal ini dikarenakan, hidup terus berlanjut sementara tugas kita untuk memenuhi kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Kita tidak mungkin lantas berhenti berkarya dan bekerja setelah semua kebutuhan pokok fisik kita terpenuhi.
Nah, dalam perjalanan hidup kita, setelah kebutuhan pokok fisik terpenuhi, kita akan menemui dua cabang jalan yang berbeda. Cabang yang pertama menuntun kita pada pemenuhan kebutuhan spiritual dan kebahagiaan, sedangkan cabang yang kedua menjerumuskan kita pada kebahagiaan yang semu alias kesengsaraan.
Pikiran Menjadi Sumber Kesengsaraan
Kembali penulis tekankan, kita, sebagai manusia, merupakan makhluk sosial yang kehidupannya dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Bahagia atau tidaknya kita tergantung pada bagaimana kita menghadapi kehidupan sosial.
Berhubung kita hidup di lingkungan sosial yang hedonis, maka persepsi kita dipengaruhi oleh logika hedonisme. Dalam persepsi budaya hedonis, yang menentukan kebahagiaan seseorang adalah prestise. Dalam budaya tersebut, seseorang akan memiliki prestise manakala ia memiliki gaya berbusana, pergaulan, dan jabatan tertentu, dan mobil mewah. Semakin tinggi prestise, semakin bernilailah kita. Dan, semakin bernilai kita di mata orang lain, semakin bahagialah kita.
Singkatnya, persepsi kita mengenai kebahagiaan didikte oleh gaya hidup yang hedonis. Dalam gaya hidup yang hedonis, kebahagiaan kita ditentukan oleh penilaian orang lain terhadap kita. Kita akan bahagia manakala orang lain menilai kita sebagai orang yang sukses. Kita akan bahagia manakala orang lain memuji keberhasilan kita, memuji rumah, mobil, dan jabatan kita. Akhirnya, kita hidup hanya untuk memenuhi penilaian orang lain!
Tidak mau, kan, kebahagiaan Anda ditentukan oleh penilaian orang lain terhadap diri Anda?
Nah, indikasi bahwa kita memilih cabang yang kedua, cabang yang menjerumuskan kita pada kebahagiaan semu yaitu saat kebahagiaan kita ditentukan oleh penilaian orang lain terhadap kita. Lebih jauh, indikasi bahwa kita memilih cabang yang kedua yaitu saat pikiran dan persepsi kita didikte oleh kebudayaan yang hedonis. Kita tidak memiliki kuasa terhadap pikiran dan persepsi kita sendiri. Pikiran kita disibukkan oleh pemenuhan kebutuhan sampingan seperti memiliki mobil mewah yang, di antara tetangga kita, hanya kita yang mampu membelinya. Perasaan kita dipenuhi oleh keinginan untuk terus tampil sempurna di depan orang lain. Akibatnya, saat orang lain tampil lebih sempurna daripada kita, kita pun merasa sedih dan sengsara. Dan, pada saat itulah, pikiran kita menjadi pedang yang menghancurkan diri kita.
Pikiran Menjadi Sumber Kebahagiaan
Lalu, bagaimana cara terlepas dari budaya hedonis yang menguasai pikiran dan persepsi kita? Jawabannya terletak pada kekuatan pikiran! Jika budaya hedonis mendikte persepsi kita mengenai kebahagiaan seperti yang tersebut pada bab sebelumnya, maka untuk membebaskan diri dari persepsi hedonis, kita harus merubah persepsi kita mengenai kebahagiaan.
Pada kenyataannya, kebahagiaan bukan ditentukan oleh seberapa mewah mobil yang kita miliki, bukan pula oleh apa merek busana yang kita kenakan. Kebahagiaan sejati adalah saat kebutuhan pokok fisik dan kebutuhan spiritual kita terpenuhi.
Nah, rubahlah persepsi Anda tentang kebahagiaan seperti tersebut di atas. Sadari dan syukuri bahwa kebutuhan pokok fisik Anda telah terpenuhi. Anda sudah menjadi orang yang bahagia tanpa perlu mobil yang mewah, rumah yang besar, dan jabatan yang tinggi, dan tanpa perlu menyaingi kemewahan orang lain.
Saat Anda menyadari bahwa kebutuhan pokok Anda terpenuhi, Anda pun mengerti bahwa sekaranglah saatnya untuk memenuhi kebutuhan spiritual Anda. Kebutuhan spiritual dapat Anda penuhi dengan terus bersyukur, berpikir positif, dan tidak pernah mengeluh. Lebih jauh, kebutuhan spiritual dapat Anda penuhi dengan terus mengembangkan kesadaran Anda dan terus berkarya.
Saat kebutuhan pokok fisik kita terpenuhi, apa yang menentukan kebahagiaan selanjutnya adalah pikiran kita. Bahagia atau sengsaranya kita tergantung pada bagaimana kita mengolah pikiran kita. Pikiran yang positif, selalu bersyukur, tidak mengeluh, dan tidak terpengaruhi oleh kebudayaan yang menghancurkan kita akan membawa kita pada kebahagiaan yang hakiki. Sebaliknya, pikiran yang negatif, selalu mengeluh, dan tidak pernah bersyukur akan membawa kita pada kebahagiaan semu dan kesengsaraan.
Nah, sekarang, sudahkah Anda bahagia? Jangan ragu untuk berkomentar J